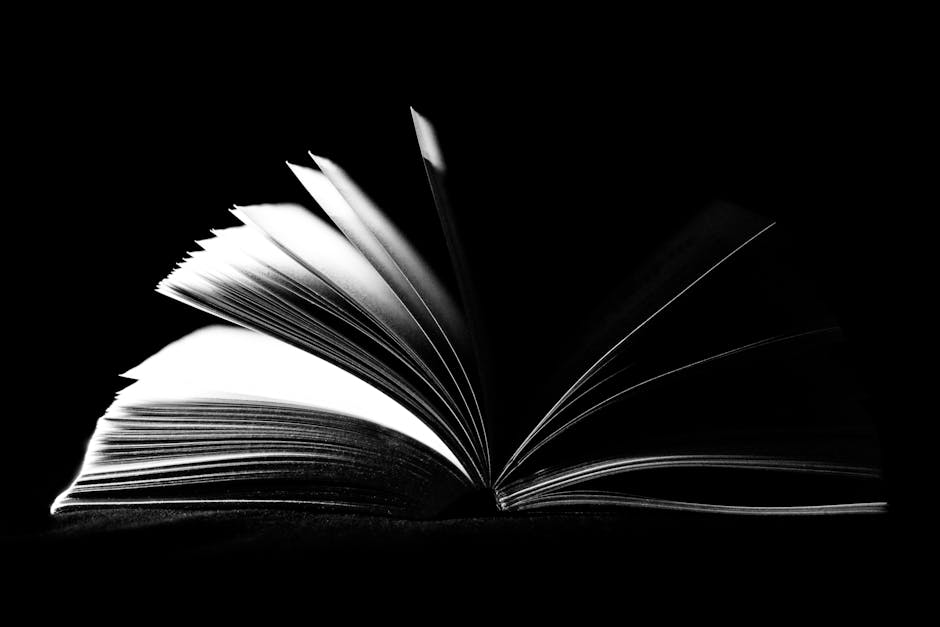Aku selalu membayangkan usia dua puluhan akhir adalah masa kebebasan, masa untuk menapaki puncak gunung dan menuliskan kisah perjalanan di belahan dunia lain. Koper sudah siap, tiket penerbangan ke Timur Tengah sudah di tangan, dan jiwaku melayang dalam euforia kemerdekaan yang sebentar lagi terwujud. Sayangnya, takdir memiliki skenario yang jauh lebih dramatis dari yang kubayangkan.
Satu panggilan telepon mendadak mengubah segalanya; Ayah ambruk dan harus menjalani perawatan intensif, sementara toko bahan bangunan kecil yang menjadi sandaran hidup kami ternyata menyimpan tumpukan utang yang tak terduga. Dalam sekejap, peta perjalananku robek, digantikan oleh tumpukan faktur yang menuntut penyelesaian segera.
Aku sempat tenggelam dalam penolakan yang dingin, merasa dicurangi oleh semesta karena impian yang sudah di depan mata harus kulepaskan. Bagaimana mungkin aku, yang baru lulus dan hanya tahu teori, harus memimpin kapal yang hampir karam ini? Namun, melihat wajah Ayah yang pucat dan tatapan Ibu yang penuh harap, aku tahu, aku tidak punya pilihan selain tumbuh.
Aku menjual tiket penerbangan yang selama ini kuhargai lebih dari emas, lalu menyalurkan semua tabungan perjalanan itu untuk membayar tunggakan gaji karyawan yang sudah berbulan-bulan tertunda. Keputusan itu terasa seperti mencabut paksa akar dari hatiku, tetapi anehnya, setelahnya muncul rasa lega yang belum pernah kurasakan.
Hari-hariku berubah menjadi labirin angka, negosiasi yang keras dengan pemasok, dan malam-malam tanpa tidur di depan layar komputer. Aku yang dulu hanya peduli pada estetika foto di media sosial, kini harus memahami seluk-beluk manajemen inventaris dan hukum dagang yang rumit. Rasa takut dan cemas selalu menyergap, tetapi setiap kali aku berhasil menyelesaikan satu masalah kecil, aku menemukan sepotong keberanian baru.
Proses itu mengajarkanku bahwa kedewasaan bukanlah tentang usia yang tertera di kartu identitas, melainkan tentang kesediaan kita memikul beban yang bukan milik kita sepenuhnya. Aku belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa jauh kita bisa lari, melainkan seberapa kokoh kita berdiri di tempat yang paling sulit.
Aku menyadari, drama yang kini kujalani adalah babak paling penting dalam hidupku, sebuah tantangan nyata yang jauh lebih mendalam dan jujur daripada fiksi mana pun. Inilah yang disebut orang-orang sebagai Novel kehidupan, di mana setiap air mata dan keringat adalah tinta yang tidak bisa dihapus.
Setelah beberapa bulan berjuang, toko kami memang belum sepenuhnya pulih, tetapi napasnya sudah teratur. Aku tidak lagi melihat tumpukan faktur sebagai ancaman, melainkan sebagai jejak langkah yang membuktikan bahwa aku mampu bertahan.
Mungkin aku belum bisa melihat puncak gunung yang kuimpikan, tetapi aku sudah menemukan gunung yang lebih tinggi di dalam diriku sendiri. Dan ketika Ayah akhirnya bisa kembali duduk di kursi kerjanya, menatapku dengan bangga, aku tahu pengorbanan itu sebanding. Namun, di balik senyum itu, aku masih menyimpan pertanyaan: setelah badai ini berlalu, apakah aku masih punya ruang untuk bermimpi lagi, atau apakah aku telah terlanjur menjadi seseorang yang hanya tahu cara berjuang?