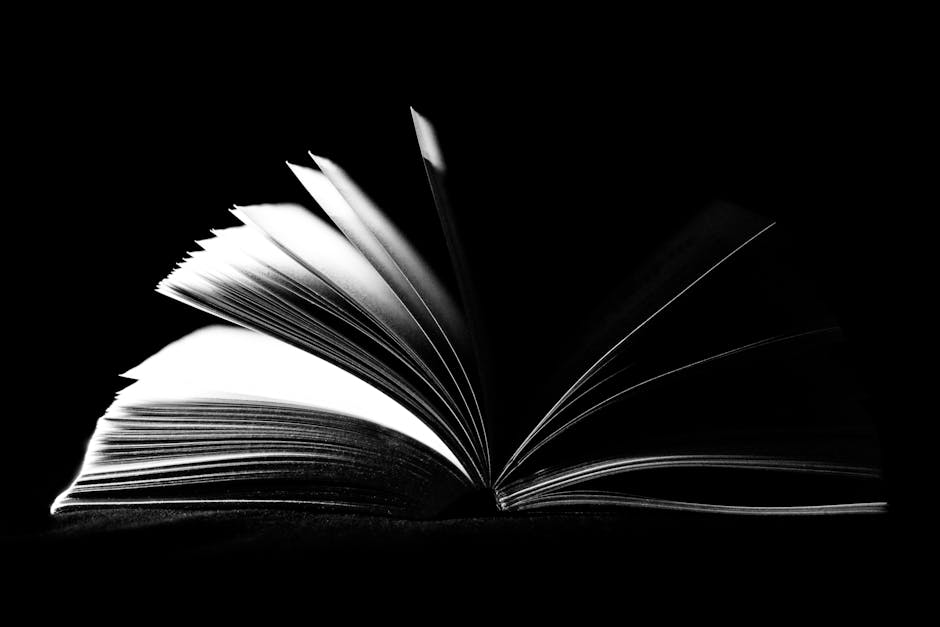Aku selalu percaya bahwa kedewasaan adalah hadiah yang datang seiring angka di kartu identitas bertambah. Aku lulus dengan predikat terbaik, merencanakan setiap langkah karier dengan presisi militer, dan yakin bahwa dunia akan tunduk pada ambisi yang kubawa. Namun, hidup punya cara yang brutal untuk mengajarkan bahwa kesombongan adalah tirai tipis di hadapan badai.
Badai itu datang dalam bentuk kegagalan investasi yang menghancurkan semua yang telah kubangun. Dalam semalam, gelar dan rencana cemerlangku berubah menjadi beban utang yang mencekik dan rasa malu yang tak terperikan. Aku yang dulunya berbicara tentang valuasi dan ekspansi, kini hanya bisa menatap pantulan diriku yang rapuh di jendela.
Keputusan untuk meninggalkan kota besar terasa seperti hukuman pengasingan. Aku menerima pekerjaan sebagai barista di sebuah kedai kopi kecil di kaki gunung, tempat yang tidak memiliki sinyal telepon dan hanya dikunjungi oleh penduduk lokal. Lingkungan sunyi itu memaksa telingaku untuk mendengarkan, bukan hanya diriku sendiri, tetapi juga gemerisik daun dan bisikan angin.
Awalnya, setiap hari adalah siksaan. Tangan yang terbiasa mengetik laporan kini harus membersihkan ampas kopi dan mengelap meja yang lengket. Aku merasa direnggut dari takdirku, tenggelam dalam rutinitas yang monoton dan jauh dari gemerlap impian yang pernah kubawa.
Namun, di kedai itu, aku bertemu Mbah Wiryo, seorang petani tua yang selalu memesan kopi hitam tanpa gula. Ia tidak pernah memberiku nasihat secara langsung, tetapi caranya menikmati kesederhanaan hidupnya—tanpa terburu-buru, tanpa keluh kesah—menampar kesadaran yang selama ini tertidur. Aku mulai menyadari bahwa kegagalan finansialku bukanlah akhir, melainkan awal.
Aku perlahan belajar bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan fondasi untuk melihat dunia secara jujur. Aku mulai berbicara tulus dengan para pelanggan, mendengar kisah-kisah mereka yang jauh lebih berat dari sekadar kehilangan uang, namun mereka menjalaninya dengan senyum yang utuh.
Di sinilah babak baru itu dimulai. Aku menyadari bahwa seluruh perjalanan ini, dari puncak kesombongan hingga dasar kepasrahan, adalah bagian terpenting dari sebuah fiksi pribadi. Inilah skenario terindah dalam Novel kehidupan yang harus kuterima dan kuresapi.
Kedewasaan yang sesungguhnya bukan tentang pencapaian yang tertera di sertifikat, melainkan tentang kemampuan untuk bangkit kembali setelah terjatuh, dan yang lebih penting, kemampuan untuk menerima kekurangan diri sendiri. Aku tidak lagi mencari pengakuan; aku mencari kedamaian dalam setiap tetes kopi yang kuseduh.
Kini, aku tidak tahu apakah aku akan kembali ke kota atau tetap di sini. Yang aku tahu, Arka yang sekarang jauh lebih kaya—bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk pemahaman. Namun, ketika Mbah Wiryo tiba-tiba menitipkan sebuah buku usang yang sampulnya bertuliskan "Halaman Berikutnya," aku tahu bahwa pelajaran hidupku belum benar-benar usai.