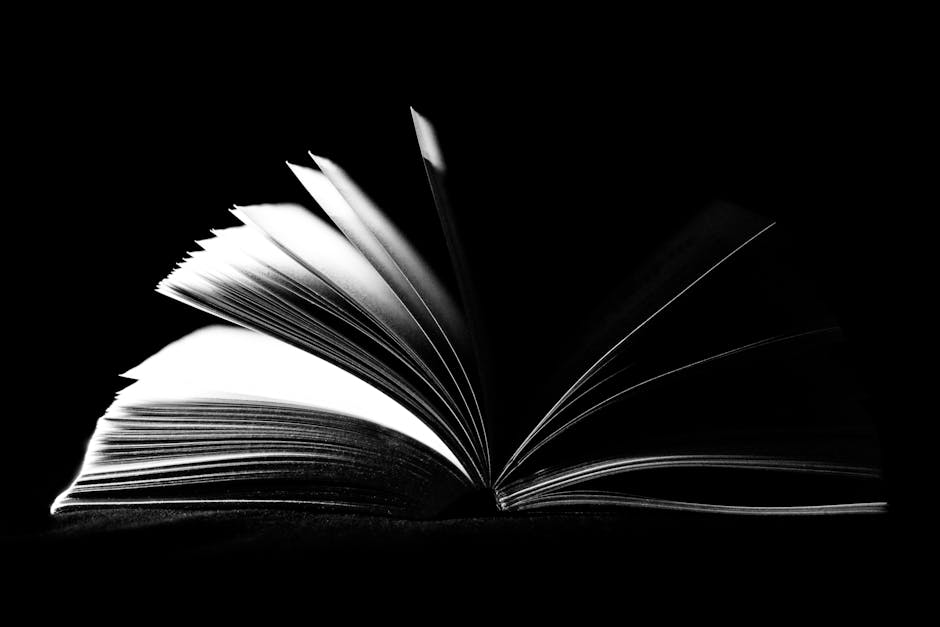Dulu, kanvas adalah satu-satunya bahasa yang aku pahami. Aku adalah Risa, sang pemimpi yang yakin bahwa warna-warna cerah akan selalu menjadi takdirku, bahwa beasiswa seni di luar negeri hanyalah soal waktu dan ketekunan. Namun, hidup punya skenario sendiri, dan seringkali ia menulis babak yang paling kelam saat kita sedang lengah.
Bayangan kelabu itu datang tak terduga, secepat kilat menyambar pohon tertinggi di taman. Ayah jatuh sakit parah, dan bersamaan dengan itu, pondasi keuangan keluarga kami runtuh. Tiba-tiba, kuas di tanganku terasa ringan, tak sebanding dengan beban tanggung jawab yang tiba-tiba mendesak di pundak.
Aku harus memilih: mengejar impian yang sudah di depan mata, atau berdiri tegak sebagai pilar penopang bagi ibu dan adik-adikku. Keputusan itu terasa seperti mencabut paksa sebagian dari jiwaku; aku menanggalkan gelar mahasiswi seni dan menggantinya dengan seragam kerja paruh waktu di sebuah kedai kopi yang ramai.
Setiap tetes kopi yang aku sajikan, setiap jam lembur yang aku jalani, adalah pengorbanan yang menusuk. Aku sering menangis diam-diam di malam hari, meratapi hilangnya masa muda dan kebebasan yang seharusnya aku nikmati. Rasanya seperti terdampar di sebuah pulau asing, jauh dari peta hidup yang telah aku susun rapi.
Namun, di tengah kelelahan fisik dan mental, aku mulai menemukan kekuatan yang tak pernah aku duga. Aku belajar mengelola rasa sakit, mengubah keputusasaan menjadi ketahanan, dan melihat nilai-nilai kecil dalam rutinitas yang monoton. Mataku kini melihat dunia dengan kedalaman yang berbeda, bukan hanya tentang estetika, tetapi tentang perjuangan nyata.
Inilah bagian terberat dan paling otentik dari Novel kehidupan-ku. Aku menyadari bahwa kedewasaan bukanlah tentang usia, melainkan tentang seberapa cepat kita mampu bangkit setelah terhempas oleh badai. Kisah ini mengajarkanku bahwa pengorbanan bukanlah kerugian, melainkan investasi terbesar dalam karakter.
Aku mulai melukis lagi, bukan di kanvas mahal, tetapi di sela-sela waktu istirahatku, menggunakan carik kertas bekas dan pensil seadanya. Subjek lukisanku kini bukan lagi bunga atau pemandangan indah, melainkan wajah ibu yang letih, atau senyum lega adikku saat aku membawakan sedikit rezeki.
Aku belum kembali ke jalur impian lamaku, namun aku telah menemukan jalur baru yang lebih kokoh. Aku tidak lagi merasa menjadi korban keadaan; aku adalah kapten yang mengendalikan kapal di tengah ombak besar. Rasa syukur atas kekuatan yang diberikan jauh lebih besar daripada penyesalan atas waktu yang hilang.
Maturitas sejati adalah menerima kenyataan bahwa beberapa mimpi harus menunggu di ruang tunggu, sementara kita sibuk membangun fondasi yang lebih kuat. Dan saat aku akhirnya bisa meraih kuas itu lagi, aku tahu, lukisan yang tercipta akan jauh lebih kaya, lebih jujur, dan penuh makna—sebab ia dilukis dengan tinta pengalaman dan air mata perjuangan.