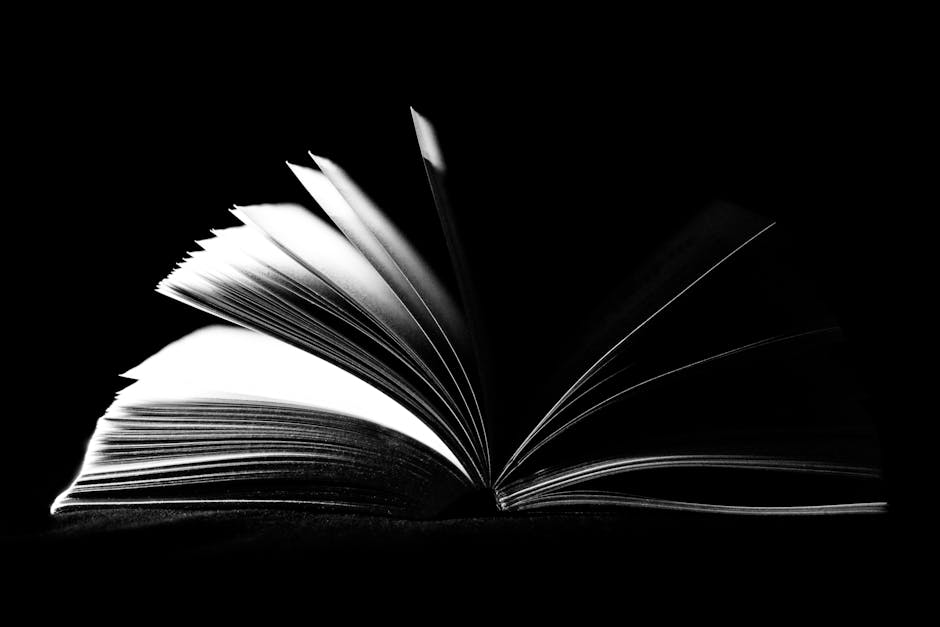Sebelum badai itu datang, aku adalah definisi dari kemudaan yang terlindungi; hidupku adalah rangkaian hari yang cerah tanpa awan, di mana masalah terbesar hanyalah memilih buku bacaan sore hari. Aku tumbuh di bawah payung kenyamanan yang dibentangkan oleh kakekku, percaya bahwa dunia beroperasi berdasarkan aturan yang sederhana dan dapat diprediksi. Namun, takdir rupanya memiliki skenario yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan.
Titik baliknya terjadi begitu cepat, secepat hembusan angin yang memadamkan lilin. Setelah kakek tiada, warisannya bukan emas atau permata, melainkan sebuah toko buku tua di pinggiran kota yang tengah sekarat. Tiba-tiba, aku yang hanya tahu cara membaca laporan keuangan fiktif di bangku kuliah, harus berhadapan langsung dengan tagihan listrik yang menumpuk dan kekejaman persaingan pasar.
Beberapa bulan pertama adalah neraka yang dingin. Aku membuat keputusan-keputusan konyol, menolak nasihat dari para pelanggan setia, dan mencoba menerapkan teori-teori buku yang sama sekali tidak relevan dengan realitas. Toko itu semakin merosot, dan rasa malu bercampur putus asa mulai menggerogoti jiwaku; aku ingin melarikan diri, kembali ke masa di mana tanggung jawab hanyalah sebuah kata asing.
Aku ingat betul malam ketika aku duduk di antara rak-rak buku yang berdebu, air mata jatuh membasahi lembar-lembar kertas tua. Saat itulah Ibu Dewi, seorang penjual jamu langganan kakek, menghampiriku tanpa berkata apa-apa, hanya menyodorkan secangkir teh hangat. Ia tidak memberiku solusi, ia hanya berkata, "Nak, hidup ini bukan soal menghindari jatuh, tapi soal seberapa cepat kamu mau berdiri setelah tersungkur." Perkataan itu, yang sederhana namun menusuk, mengubah sudut pandangku. Aku mulai belajar hal-hal yang tidak diajarkan di universitas: seni menawar dengan keras, pentingnya menjaga relasi, dan yang paling sulit, menerima bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Aku harus menjual beberapa koleksi buku langka milik kakek, sebuah tindakan yang terasa seperti pengkhianatan, namun demi napas toko yang harus terus berlanjut.
Setiap transaksi yang berhasil, setiap pelanggan yang kembali, terasa seperti kemenangan kecil dalam perang besar yang sunyi ini. Aku menyadari bahwa pengalaman ini adalah babak paling krusial dalam Novel kehidupan yang sedang kutulis; sebuah kisah yang menuntutku untuk melepaskan jubah kepolosan dan mengenakan baju baja kedewasaan.
Aku tidak lagi mencari jalan termudah, melainkan jalan yang paling jujur. Proses ini mengikis habis naifku, menggantinya dengan empati dan pemahaman yang lebih dalam tentang perjuangan orang lain. Kota yang dulu terasa senyap dan membosankan, kini menjadi panggung di mana setiap orang memainkan peran mereka, berjuang untuk bertahan hidup dengan martabat.
Toko buku itu memang belum kembali berjaya, tetapi ia stabil. Yang lebih penting, aku telah berubah. Aku belajar bahwa kedewasaan bukanlah usia yang tercantum di KTP, melainkan akumulasi dari badai yang berhasil kita lalui tanpa kehilangan arah kompas moral.
Namun, di balik stabilitas yang kuraih, ada bayangan misterius yang terus mengikutiku—sebuah surat wasiat kedua kakek yang belum pernah kubuka, tersembunyi di balik sampul buku paling tua. Surat itu mungkin menyimpan rahasia tentang mengapa kakek membiarkan toko ini hampir bangkrut, dan apakah ujian kedewasaan yang sesungguhnya baru saja dimulai.