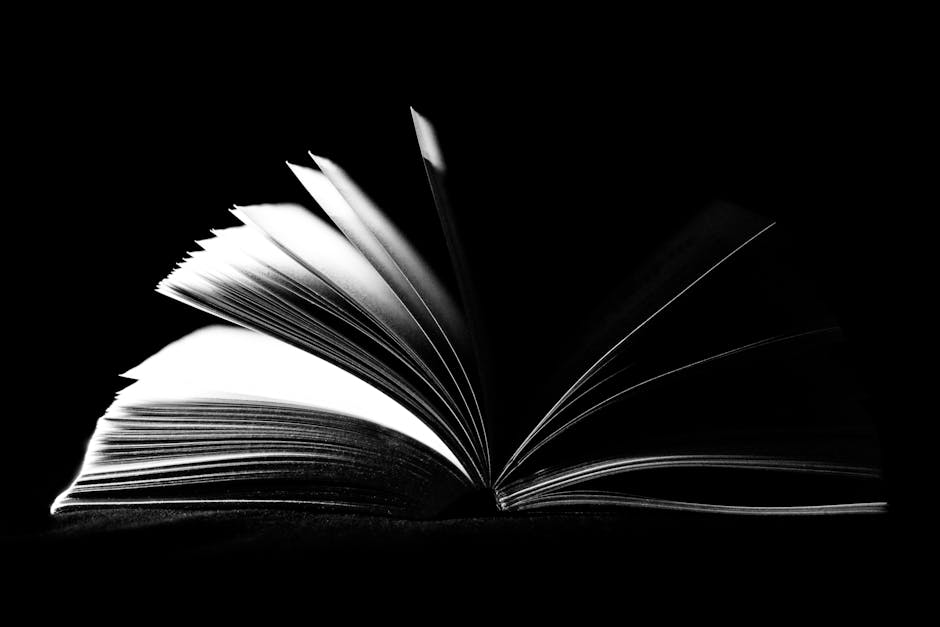Aku selalu membayangkan kedewasaan akan datang seperti pasang surut air laut: perlahan, pasti, dan seiring berjalannya waktu. Hidupku saat itu hanyalah serangkaian jadwal yang teratur, di mana keputusan terberat adalah memilih kedai kopi mana yang akan kukunjungi hari ini. Aku naif, percaya bahwa badai hanya ada di buku-buku fiksi.
Kenangan tentang panggilan telepon di tengah malam itu masih terasa dingin menusuk, memecah kesunyian malam yang biasanya tenang. Kabar bahwa Ayah jatuh sakit parah dan harus meninggalkan kemudi perusahaan kecil kami membuat duniaku seketika runtuh dan berantakan. Aku yang biasanya hanya mengurus laporan ringan, kini harus bertanggung jawab atas puluhan nasib karyawan yang bergantung pada stabilitas perusahaan.
Rasa panik memimpin setiap rapat yang kuadakan, dan angka-angka di laporan keuangan terasa seperti bahasa asing yang menakutkan, jauh dari teori yang kupelajari di bangku kuliah. Aku membuat beberapa kesalahan fatal di awal, membuat kerugian yang hampir tak tertanggulangi dan membuatku sulit tidur. Saat itu, aku menyadari bahwa kedewasaan bukanlah gelar yang didapat, melainkan medan perang yang harus dimenangkan dengan darah, keringat, dan air mata.
Malam-malamku berubah menjadi sesi belajar maraton, ditemani kopi dingin dan rasa malu yang membakar karena ketidakmampuanku. Aku mulai mendengarkan keluhan para pekerja, memahami alur produksi dari nol, dan berhenti berpura-pura tahu segalanya di depan mereka. Ketidaksempurnaan dan kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan itu justru menjadi guru terbaik.
Dalam proses merangkai kembali potongan-potongan kekacauan ini, aku menemukan kekuatan yang tak kusangka ada di dalam diriku, sebuah sumur energi yang baru kusadari keberadaannya. Setiap kegagalan, setiap tetes keringat, adalah babak baru yang ditulis tak terduga dalam takdirku. Inilah yang sesungguhnya disebut sebagai Novel kehidupan, sebuah narasi yang menuntut kita menjadi penulis, editor, sekaligus pemeran utamanya.
Waktu tidak lagi terasa lambat atau cepat; ia hanya terasa berharga, diukur dari produktivitas dan keputusan yang tepat. Tekanan yang dulu kuanggap beban kini menjadi cetakan yang membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih tangguh. Aku belajar bahwa mengorbankan kenyamanan hari ini adalah investasi untuk ketenangan dan keberlanjutan di masa depan.
Perlahan, perusahaan kembali stabil, dan senyum Ayah saat melihatku memimpin rapat dengan penuh percaya diri adalah hadiah yang tak ternilai, jauh lebih berharga dari materi apa pun. Aku mungkin belum sempurna, tetapi aku jauh lebih matang dari diriku yang dulu yang hanya mengenal zona nyaman. Kehilangan rasa aman telah memberiku fondasi yang kokoh, jauh di luar dugaan.
Sekarang, ketika aku menatap cermin, aku melihat bayangan yang berbeda; bukan lagi pemuda yang takut akan ketidakpastian, melainkan seseorang yang siap menerima babak apa pun yang akan datang. Tantangan berikutnya mungkin sudah menanti di tikungan jalan, namun kini aku tahu bagaimana cara memegang pena takdirku sendiri, siap menulis kisah selanjutnya dengan keberanian.