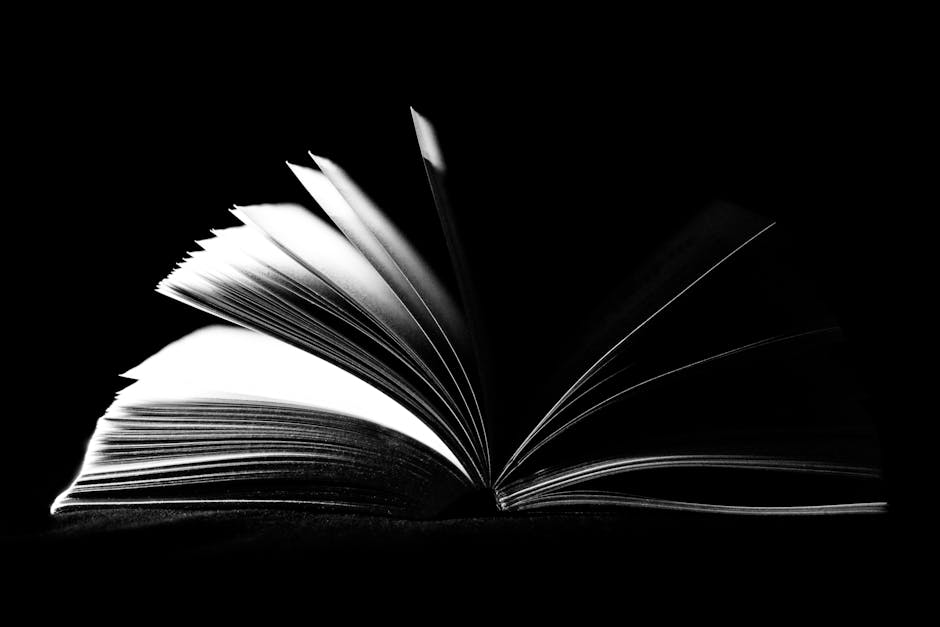Aku selalu percaya bahwa kedewasaan adalah garis finis yang dicapai setelah serangkaian prestasi gemilang, seperti tangga yang harus dipanjat hingga puncaknya. Dulu, ambisiku begitu besar, aku melihat kegagalan sebagai aib yang harus dihindari, dan kesempurnaan adalah satu-satunya mata uang yang berlaku dalam hidupku. Dunia terasa seperti kanvas yang siap kuwarnai dengan pencapaian yang memukau.
Namun, semesta memiliki cara yang brutal untuk mengoreksi pandangan picikku. Saat surat penolakan itu tiba, merenggut kesempatan emas yang telah kurajut bertahun-tahun, dunia yang kukenal mendadak runtuh menjadi debu. Rasanya seperti didorong jatuh dari ketinggian tanpa sempat berpegangan, meninggalkan luka menganga yang tidak terlihat.
Beberapa minggu pertama adalah masa-masa kegelapan yang pekat, di mana aku hanya mampu meringkuk dan mempertanyakan semua yang telah kuusahakan. Aku merasa dikhianati oleh takdir dan oleh diriku sendiri yang dianggap kurang gigih. Ego yang selama ini kujaga rapi hancur berkeping-keping, digantikan oleh rasa malu yang menusuk hingga ke tulang.
Titik baliknya datang di suatu pagi yang sunyi, ketika aku menyadari bahwa air mata dan ratapan tidak akan pernah mengembalikan waktu atau mengubah keputusan yang sudah dibuat. Aku melihat pantulanku di cermin; bukan lagi sosok ambisius yang sempurna, melainkan seseorang yang rapuh namun masih bernapas. Saat itulah aku memutuskan, jika aku tidak bisa mendapatkan jalan yang kuharapkan, aku akan membangun jalan yang baru.
Proses membangun kembali diri itu jauh dari kata glamor; itu adalah proses yang kotor, penuh keraguan, dan seringkali menyakitkan. Aku harus menerima pekerjaan yang dulu kuanggap remeh dan belajar dari nol, menghadapi tatapan simpati yang menusuk dan bisikan keraguan dari orang-orang. Setiap hari adalah perjuangan untuk menaklukkan rasa rendah diri yang terus membayangi.
Aku mulai memahami bahwa setiap kesulitan, setiap penolakan, dan setiap air mata yang jatuh adalah tinta yang tak terhindarkan dalam naskah kehidupan ini. Ini adalah babak penting dalam Novel kehidupan yang harus aku tulis sendiri, bukan sekadar cerita tentang kemenangan, melainkan tentang ketahanan jiwa. Kedewasaan bukanlah tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar menari di tengah hujan lebat.
Seiring berjalannya waktu, aku menemukan bahwa aku tidak lagi mengejar standar kesuksesan yang ditetapkan orang lain, melainkan berusaha memenuhi janji pada diriku sendiri untuk terus bertumbuh. Aku belajar menghargai proses, bukan hanya hasil, dan menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan. Luka lama itu kini menjadi peta yang menunjukkan seberapa jauh aku telah berjalan.
Kedewasaan sejati, ternyata, adalah menerima kerapuhan diri tanpa merasa perlu menyembunyikannya, dan memiliki empati terhadap perjuangan orang lain karena kita pernah terpuruk sama dalamnya. Aku tidak lagi sama dengan Risa yang dulu, yang mengukur harga dirinya dari capaian di atas kertas. Aku sekarang adalah Risa yang terbentuk dari puing-puing.
Kini, aku berdiri di persimpangan baru, tidak lagi takut gagal, tetapi takut jika aku berhenti mencoba dan belajar. Bekas luka itu adalah pengingat abadi bahwa kekuatan terbesar seseorang bukan terletak pada seberapa tinggi ia terbang, melainkan pada seberapa cepat ia mampu bangkit setelah terjatuh. Apakah aku sudah dewasa sepenuhnya? Mungkin tidak, tapi setidaknya, aku sudah tahu bagaimana cara hidup dengan jujur.