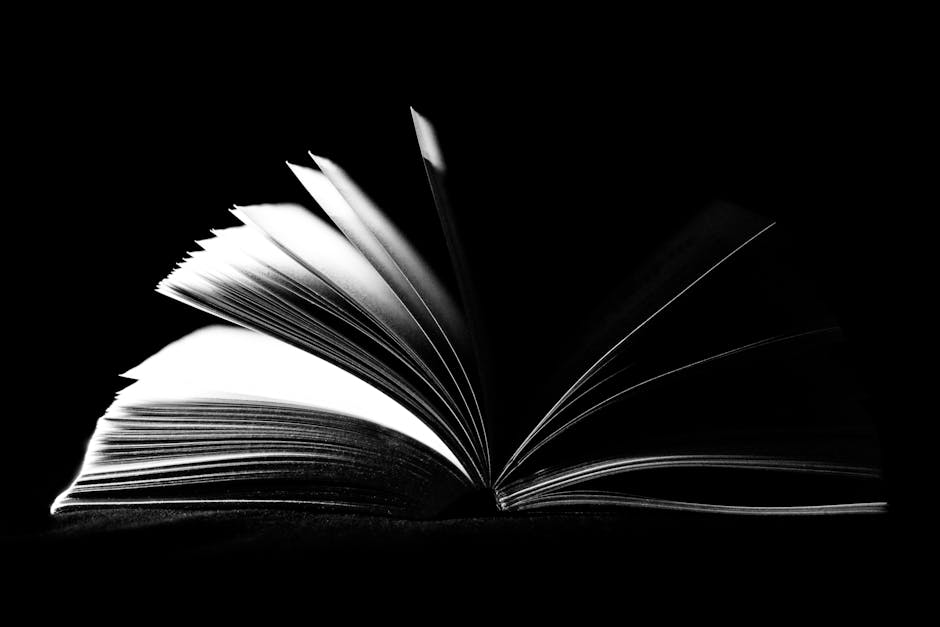Aku selalu membayangkan kedewasaan sebagai garis finis yang gemerlap, dicapai setelah menamatkan pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan impian. Dalam bayanganku, prosesnya rapi, terencana, dan penuh tepuk tangan; aku tidak pernah menyadari bahwa kedewasaan yang sesungguhnya lahir dari kekacauan, dari malam-malam tanpa tidur dan keputusan yang memeras air mata. Aku hidup dalam gelembung kaca yang kurawat dengan hati-hati, hingga satu panggilan telepon memecah segalanya.
Suara Ayah di seberang sana terdengar berat, jauh dari nada ceria yang biasa kudengar, mengabarkan bahwa fondasi bisnis yang kami anggap kokoh ternyata hanya tumpukan pasir. Seketika, beasiswa ke luar negeri yang sudah ku genggam, tiket menuju masa depan ideal, terasa hampa. Mimpi yang telah kubangun bertahun-tahun harus kukorbankan demi menopang puing-puing yang tersisa di rumah.
Melepaskan mimpi itu terasa seperti amputasi perlahan; aku harus memotong bagian terbaik dari diriku demi menyelamatkan yang lain. Aku menukar buku-buku tebal dan diskusi filosofis dengan seragam kusam dan pekerjaan di bagian administrasi sebuah gudang yang jauh dari hingar bingar kota. Dunia terasa dingin, dan untuk pertama kalinya, aku harus berhadapan langsung dengan kejamnya tagihan yang menumpuk.
Setiap pagi, saat fajar bahkan belum menyentuh cakrawala, aku sudah harus berjuang melawan rasa kantuk dan beban tanggung jawab yang terasa terlalu besar untuk pundakku. Ada rasa malu yang menusuk saat melihat teman-teman sebaya mengunggah foto-foto pencapaian mereka, sementara aku bergumul dengan laporan stok dan interaksi yang menuntut kesabaran ekstra. Aku sering bertanya, mengapa jalan hidupku harus berkelok tajam seperti ini.
Namun, di tengah kelelahan fisik dan mental itu, aku mulai menemukan sesuatu yang hilang dari diriku yang dulu: empati dan ketahanan. Aku belajar bahwa kesopanan sejati bukan hanya tentang etika di meja makan, tetapi tentang bagaimana aku memperlakukan orang yang gajinya jauh lebih kecil dariku, bagaimana aku bereaksi saat menghadapi kegagalan yang bukan salahku.
Aku menyadari bahwa setiap kesulitan yang kualami, setiap kegagalan yang kuterima, adalah babak penting dalam proses pendewasaan. Ini adalah skenario yang mendewasakan, bagian tak terpisahkan dari apa yang orang sebut sebagai Novel kehidupan. Aku bukan lagi Risa yang manja; aku adalah Risa yang mampu bertahan, yang memahami bahwa kerapuhan juga bisa menjadi sumber kekuatan.
Melalui pekerjaan kasar dan penolakan yang tak terhitung, aku belajar seni menelan ego, memahami bahwa meminta bantuan bukanlah kelemahan, melainkan pengakuan jujur atas keterbatasan manusiawi. Kedewasaan ternyata bukan tentang tahu segalanya, melainkan tentang berani mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa dan tetap melangkah maju.
Bekas luka finansial dan emosional ini, yang dulu ingin kusembunyikan, kini menjadi peta yang menunjukkan sejauh mana aku telah berjalan. Mereka adalah bukti nyata bahwa aku pernah jatuh, tetapi aku selalu menemukan cara untuk bangkit, sedikit demi sedikit, hari demi hari.
Mungkin aku belum mencapai garis finis yang gemerlap itu, tetapi aku sudah mendapatkan hadiah yang jauh lebih berharga: sebuah jiwa yang ditempa oleh api kesulitan. Dan kini, ketika badai berikutnya datang, aku tahu aku tidak akan lagi bersembunyi. Aku akan berdiri tegak, siap menyambut tantangan itu, karena aku sudah tahu bahwa pelajaran terbesar dalam hidup selalu datang dalam bentuk pengorbanan yang tak terduga.